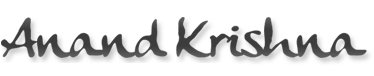Uraian berikut ini Kutipan dari buku : “Ananda’s Neo SELF – LEADERSHIP – Seni Memimpin Diri bagi Orang Modern” – Halaman 127 – 133 membahas tentang definisi budaya melalui sudut pandang penulisnya. Mari sama-sama kita simak apa penjelasanan Anand Krishna terkait dengan definisi budaya tersebut.
“The truest test of civilization,
culture and dignity is character and not clothing.”
Tes (batu uji atau tolak ukur) suatu peradaban,
Budaya, dan martabat (manusia)
adalah karakter (watak), bukan pakaian.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Bapak Bangsa India/ Tokoh Ahimsa
Dan karakter adalah hasil dari pematangan jiwa – mengunakan bahasa Ki Hadjar Dewantara, jiwa yang sudah masak, sudah mature, sudah berkembang.
Jadi, budaya bukanlah urusan seni, kuliner, peninggalan sejarah, museum, dan tepat wisata semata. Bulkan juga urusan norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan dalam mayarakat, tetapi uruan watak manusia, urusan watak yang membuat sesorang menjadi bijak.
Seorang pejabat tinggi, menteri, bahkan seorang usahawan, industrialis, pendidik, seorang professional dibidang apa saja, termasuk karyawan biasa, semuanya mesti berbudaya, berkarakter yang baik. Barulah mereka disebut orang-orang yang beradab.
Soal kepercayaan seseorang, menurut saya, adalah urusan pribadi dia. Tetapi oal budaya adalah urusan masyarakat. Ebab orang yang tidak berprilaku baik, tidak berbudaya, tidak beradab, kemudian berinteraksi dengan orang lain, dapat merusak tatanan sosial.
Kita tidak dapat menilai kepercayaan atau keimanan sesorang terhadap Tuhan. Iapa yang dapat menilainya kecuali Gusti sendiri? Seseorang boleh aja menganggap dirinya sudah beriman karena rajin beribadah. Kita boleh menilainya demikian karena melihat dia keluar masuk tempat ibadah. Namun, adakah jaminan bahwa segala apa yang tampak pada permukaan itu telah menyentuh hatinya?
Adakah jaminan bahwa setiap orang yang berkepercayaan dan rajin beribadah sudah berkarakter baik dan berwatak mulia?
Biarlah Gusti menilai kepercayaan dan keimannan kita, karena itu adalah hakNya, prerogatifNya. Kita tidak boleh dan tidak bisa merampas hak itu. Adalah sangat egois jika kita hidup dalam ilusi atau dalam halusinasi bahwa kita bisa menila kepercayaan dan keimanan seseorang.
Adalah soal prilaku manusia yang dapat kita nilai. Adalah soal beradab dan berbudaya yang dapat kita nilai, karena semua itu merupakan perkara duniawi. Urusan sosial, urusan kita bersama.
Betapa berbudayanya dan beradabnya seseorang dapat dinilai dari gerak-geriknya, dari caranya berinteraksi dengan orang lain, dari integritas dirinya ketika menghadapi suatu tantangan berat.
Kata tehzib dalam bahasa Persia Kuno merujuk pada perkara budaya dan adab pula. Seseorang yang ber-tehzib dihormati masyarakat karena prilkakunya, karena wataknya.
Jika kita membedah kata “budaya” lebih lanjut, maka sesungguhnya istilah ini merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa ansekerta, Buddhi dan Hridaya.
Kata “Budi” dalam bahasa kita berasal dari Buddhi, yang berarti penghalusan Gugusan Pikiran dan Perasaan, Manas atau Mind. Penghalusan sempurna; penghalusan yang terjadi sedemikian rupa sehingga Gugusan Pikiran dan Perasaan, Manas atau Mind bertransformasi total menjadi Budi atau Buddhi.
Kemudian kata kedua, Hridaya, berarti jantung, yang dalam konteks ini bukanlah organ jantung, tetapi jantung Terdalam, tempat Rasa Terdalam berkembang. Dan. Rasa Terdalam itu adalah Kasih.
Sungguh hebat para leluhur yang telah menciptakan kata ini! Dalam atu kata “budaya” tersimpan arti yang sungguh luar biasa dan maha luas. Seseorang yang berbudaya adalah “eorang yang berpikiran jernih, berperasaan halus, dan wataknya berlandaskan kasih.”
Betapa kayanya budaya asal kita yang bisa menciptakan istilah-istilah semacam ini. Seorang yang berbudaya adalah seorang yang berwawasan luas, tidak mengotak-ngotakkan manusia berdasarkan suku, ras, kepercayaan, warna kulit, dan sebagainya. Dan, di ata segalanya, ia menjadikan kasih sebagai landasan hidupnya.
Demikian dengan kasih sebagai landasan hidupnya, semua nilai-nilai mulia lain ikut memperkaya hidupnya. Seseorang yang mengasihi jelas tidak bisa mennidas, tidak bisa bertindak tidak adil. Seseorang yang mengasihi sudah pasti jujur, tidak menipu atau merampas hak orang. Ia tak akan memaksa orang untuk menerima kehendaknya. Ia tidak akan menggunakan kekerasan atau tipu muslihat untuk mencapai suatu tujuan.
Nah, sekarang dengan menggunakan definisi budaya seperti itu, definisi yang sesungguhnya, marilah kita terlebih dahulu menilai diri kita masing-masing, “Adakah kita semua sudah berbudaya? Udah beradab?”
Adakah kita masih mempersoalkan kepercayaan dan keimanan orang dan malah tidak memperhatikan wataknya? Watak boleh buruk, asal kepercayaan ama, asal seiman; apakah seperti itu semboyan kita? Jika demikian, mari kita setuju untuk tidak setuju. Maaf, tulisan ini bukan untuk Anda. Saya menghormati pilihan Anda, keputusan Anda, cara pandang Anda, tapi maaf, cara pandang saya berbeda. Cara pandangmu bagimu, cara pandangku bagiku.
Masih terkait dengan budaya asal Nusantara, sungguh ironis bahwa sebagian besar masyarakat kita masih mengira bahwa budaya asal kita itu berdasar pada Hinduisme, Budhisme, dan/atau Animisme yang diimport dari India.
Demikian, mereka hendak membenarkan impor budaya-budaya lain, sebab “ bagaimana juga, toh kita tidak memiliki budaya asli, sejak dulu semuanya impor” demikian dalil mereka. Tidak, tidak benar. Mereka tidak tahu sejarah budaya, mereka tidak pernah membaca tentang penemuan-penemuan baru (baca juga Wisdom of Sundaland dan Indonesia Jaya oleh penulis – Ed.)
Tidak, kita tidak mengimpor budaya dari India.
Ya, kita, seperti yang sudah saya jelakan di bagian lain, berada dalam wilayah bperadaban yang atu dan sama, yaitu wilayah peradaban Sindhu, yang kemudian disebut Hindu oleh orang-orang Parsi, Shintu oleh orang-orang China, Indos atau Indus oleh Yunani dan mereka yang berbahasa Latin. Dari kata itulah kemudian lahir kata India, Hindia, Indo, Indies dan sebagainya.
Jadi dalam konteks ini, Sindhu tidak merujuk pada suatu kepercayaan tertentu, tapi pada
Saya sudah banyak menulis tentang hal ini dalam buku-buku lain, kiranya tidak perlu saya ulangi lagi.
Sayangnya, pendapat bahwa kita mengimpor budaya dari India juga sering dilontarkan oleh para pakar yang tidak mempersoalkan hal terebut, namun tetap memercayainya. Kiranya mereka mulai membaca penemuan-penemuan baru yang terkait dengan Shindu atau Indus Civilization.
Kesalahpahaman juga terjadi di antara Kita. Contohnya, banyak yang mengira bahwa telah terjadi Jawanisasi di pulau-pulau lain.
Setelah menyelami beberapa karya kuno Nusantara, di antaranya Slokantara, Sara-Samuccaya, Sevaka Dharma dan lain-lain (ulasan kembali oleh penulis sudah diterbitkan dalam 3 jilid berukuran besar dengan Judul Dvipantara Dharma Sastra, Dvipantara Yoga astra, dan Dvipantara Jnana Sastra – Ed.) termasuk epos besar I La Galigo dari tanah Bugis, sekarang saya tidak setuju sama sekali dengan istilah Jawanisasi.
Di Jawa, jika kita menghormati tanah air sebagai IUbu Pertiwi, maka di Minang pun ada konsep Bundo Kandung. Budaya ali pulau-pulau se-Nusantara sesungguhnya masih ama dengan budaya Jawa, budaya Sunda – budaya Peradaban Hindia. Leluhur kita menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban yang sama.
Ya, yang terjadi adalah bahwa di Jawa nilai-nilai budaya kuno tersebut maih dilestarikan oleh berbagai kalangan. Di Bali masih, barangkali di beberapa pulau lain pun masih ada segmen-segmen yang masih melestarikannya. Sementara itu, banyak pulau yang sangat terpengaruh oleh budaya luar merasa tidak perlu melestarikan nilai-nilai kuno yang sesungguhnya masih sangat relevan dan lebih cocok dengan watak kita.
Sumber ;
Judul Buku : “Ananda’s Neo SELF LEADERSHIP – Seni Memimpin Diri bagi Orang Modern”
Penulis : Anand Krishna
Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2017
Buku “Ananda’s Neo SELF – LEADERSHIP – Seni Memimpin Diri bagi Orang Modern bis adi dapatkan melalui: WA Order: 087885111979